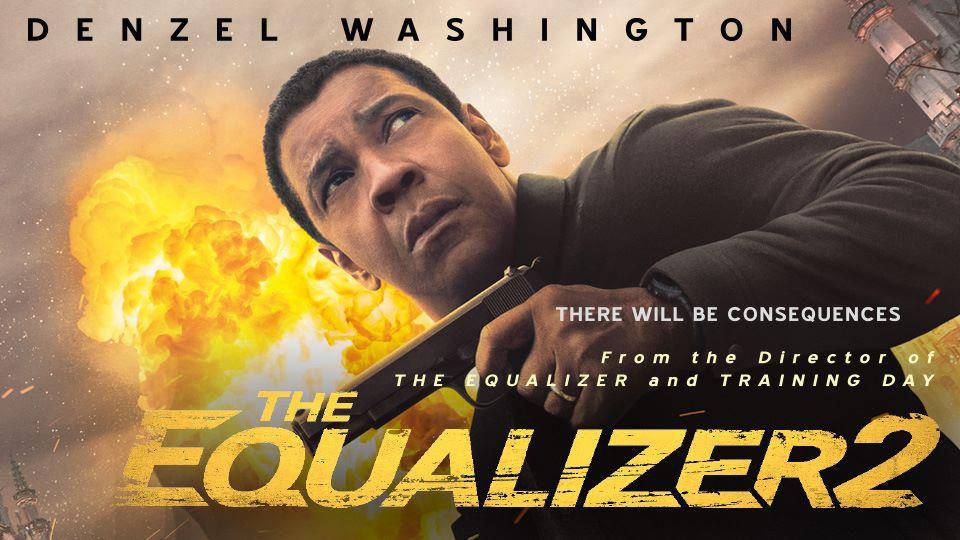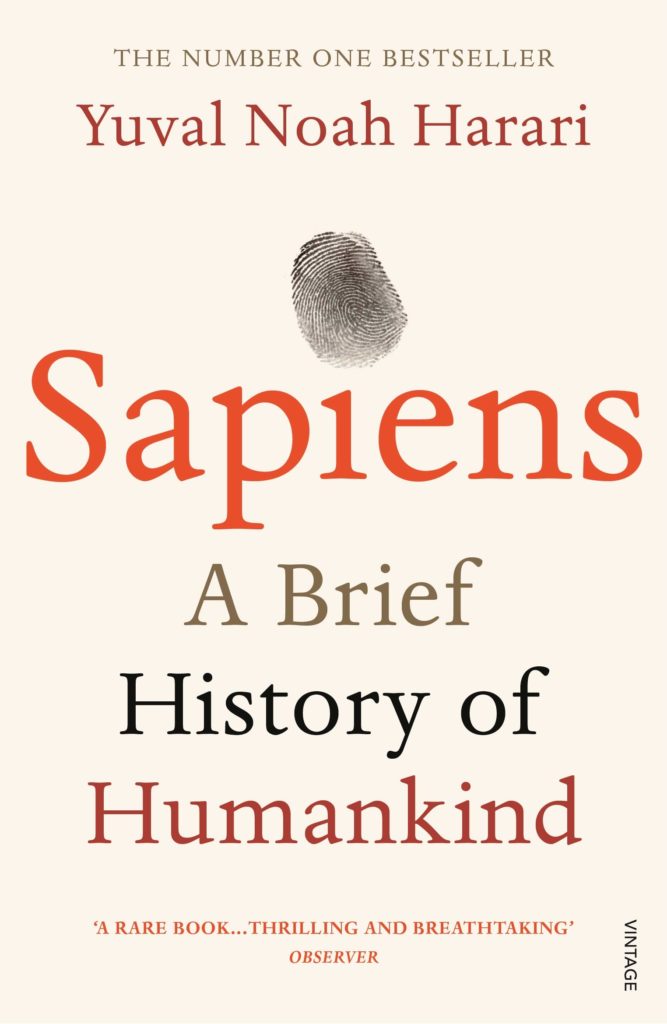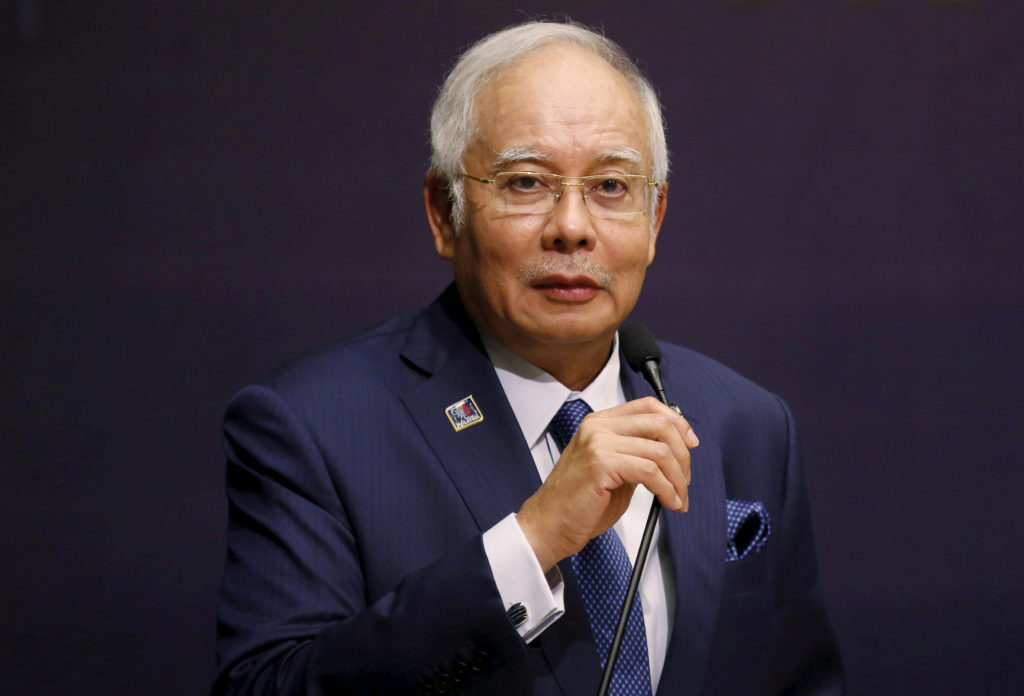Pada 16 Julai 2020 sekitar jam 12 petang, saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan Wern Han salah seorang ahli kumpulan GE-Global di Facebook. Beliau berkongsi pautan berita dari Malaysiakini tentang jawapan menteri pendidikan, Radzi Jidin di Parlimen yang menyatakan bahawa program PPSMI tidak akan dihidupkan semula, dan pengajaran tulisan Jawi akan diteruskan.
Saudara Wern Han mempertikaikan bahawa hampir semua ahli parlimen melengkapkan pengajian mereka di luar negara, dan mereka belajar menggunakan Bahasa Inggeris. Beliau tidak mengemukakan apa-apa data terhadap dakwaan ini, saya anggap ia adalah kepercayaan beliau. Namun, jika dilihat dengan lebih dekat, pertikaian beliau ini jika benar, membuktikan bahawa kita tidak perlukan PPSMI untuk berjaya belajar di luar negara dan menjadi menteri. Kerana tentunya ahli parlimen yang 40% adalah golongan yang berumur lebih 60 tahun menerima pendidikan sebelum PPSMI dilaksanakan pada tahun 2003.
Saya masih ingat, pada tahun 2003 itu saya berada di tingkatan 1, terdapat banyak kekeliruan, bukan sahaja pelajar, malah guru-guru. Pada peringkat awal itu, saya masih ingat, semasa peperiksaan masih diberikan pilihan, ketika PMR dan SPM kertas-kertas subjek seperti Sains, Matematik, Fizik, Kimia, dan Biologi semuanya dwi-bahasa. Pelajar boleh memilih hendak menjawab dalam Bahasa Inggeris atau Melayu. Kertas soalan dan jawapan juga dwi-bahasa. Kami pelajar ketika itu, benar-benar merasakan bahawa kami adalah tikus makmal untuk menguji polisi pendidikan negara.
Saudara Wern Han kemudian bertanya, adakah kita perlu berhenti menggunakan Bahasa Inggeris untuk mengajar? Saya merasakan beliau keliru. Di Malaysia kita tentulah belajar dalam bahasa nasional, itu tidak bermakna kita tidak belajar bahasa Inggeris sebagai satu subjek berasingan. Wern Han kemudian menambah bahawa beliau faham kepentingan bahasa kebangsaan (bagi saya, baguslah jika faham), tapi beliau berkata kita juga perlu tahu bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai bahasa antarabangsa. Beliau memberi contoh ketika pelancong datang ke Malaysia, kita perlu gunakan bahasa Inggeris, jika kita tidak fasih, bukankah ini akan meninggalkan persepsi buruk terhadap Malaysia?
Disini kelihatan beliau masih keliru. Malaysia menurut EF English Proficiency Index (EF EPI) pada tahun 2019 berada di tangga ke 26, dikategorikan sebagai high proficiency bersama negara maju seperti Switzerland (Switzerland adalah negara ke-2 termaju dalam dunia selepas Norway menurut World Population Review pada tahun 2020). Malah Malaysia dalam indeks EF EPI lebih baik dari Perancis (31), Hong Kong (33), Korea Selatan (37) yang dikategorikan sebagai moderate proficiency. Jika kita ukur sekadar di Asia, Malaysia di tempat ke-3 selepas Singapura ditempat pertama dan Filipina di tempat kedua.
Baik, berbalik kepada hujah pelancong asing Wern Han, pelancong biasanya mahukan informasi-informasi tempatan yang mudah seperti arah dan lokasi, ini semestinya mudah dijawab bagi warga Malaysia yang merupakan negara ke-3 di Asia yang mempunyai tahap kebolehan bahasa Inggeris yang tinggi. Pelancong bukan mahu menilai tatabahasa bahasa Inggeris kita, dan kita mencapai semua ini tanpa pun kita bergantung kepada polisi PPSMI. Wern Han kemudian berkongsi pengalamannya melancong ke Thailand, dan terpaksa menggunakan aplikasi Google Translate sepanjang masa. Bagi saya ini bukan hujah, jika Thailand bermasalah suruhlah Thailand yang melaksanakan PPSMI bukan Malaysia. Mengapa kita perlu makan ubat kepada penyakit yang kita tidak hidapi?
Akhirnya Wern Han berkata bahawa dia hanya menyatakan jika kita tidak boleh bertutur bahasa Inggeris kita akan ada masalah komunikasi dengan orang asing, dan dia tidak menyalahkan Malaysia dalam hal ini. Belajar bahasa Inggeris tidak akan menyelesaikan persoalan bahasa ni negara kita tambahnya lagi. Dan pada ketika itu saya pun bersetuju.
Artikel ini pertama kali diterbitkan di blog Meniti Jambatan Masa.
Author of several books including Berfikir Tentang Pemikiran (2018), Lalang di Lautan Ideologi (2022), Dua Sayap Ilmu (2023), Resistance Sudah Berbunga (2024), Intelektual Yang Membosankan (2024), Homo Historikus (2024), DemokRasisma (2025), dan Dari Orientalisma Hingga ke Genosida (2025). Fathi write from his home at Sungai Petani, Kedah. He like to read, write and sleep.